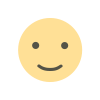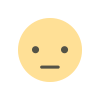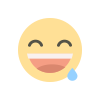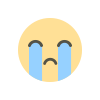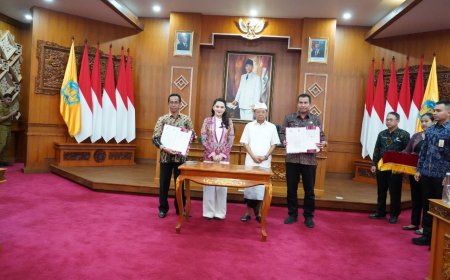Nang Lecir dan Langit yang Terbelah.

Pagi di desa Kahuripan selalu datang dengan suara gemericik air irigasi dan derit bambu yang dipakai menahan burung di pematang. Namun hari itu berbeda. Langit yang biasanya tenang kini berisik. Sebuah benda melayang, mengeluarkan suara menderu seperti tawon raksasa.
Nang Lecir, seorang petani sepuh yang setia menggantungkan hidup dari tanah warisan leluhurnya, menghentikan pekerjaannya. Tangannya yang kotor lumpur menggenggam erat cangkul, matanya menatap langit dengan kerut yang makin dalam.
“Itu teknologi terbaru,” suara berat menggema dari pinggir sawah. Seorang pria berkemeja bersih dan sepatu kulit berdiri di atas pematang. Ia adalah Tuan Tanah, pemilik lahan yang kini lebih sering tampil di layar televisi desa daripada menyentuh lumpur.
“Drone penyemprot pupuk cair. Cepat, efisien, dan tidak perlu banyak tenaga manusia. Termasuk sawahmu juga dapat jatahnya.”
Nang Lecir mengangguk pelan. Tidak setuju, tapi tak kuasa menolak. Di tangannya, Tuan Tanah meletakkan sebotol kecil cairan kimia.
“Ini untuk tikus. Supaya padimu tidak habis sebelum panen.”
Nang Lecir tidak langsung bicara. Ia hanya menatap botol itu dalam-dalam, seolah cairan di dalamnya bisa menjawab keraguan yang bergemuruh di dadanya.
"Sejak kapan alam butuh racun untuk menyeimbangkan dirinya?" pikirnya. "Tikus ada karena ada sisa panen. Ular datang memburu tikus. Burung elang menukik memburu ular. Rantai itu tidak pernah rusak sampai manusia mulai memutusnya."
Tapi siapa dia? Hanya petani renta tanpa gelar. Tidak punya kuasa menolak. Hanya bisa diam dan itu lebih menyakitkan daripada tanah yang mengering.
Malam hari, saat orang lain tidur, Nang Lecir kembali ke sawah. Ia tidak membawa botol racun, tapi bibit serai, batang pandan, dan seikat jerami. Ia tahu, bau alami dari tanaman tertentu bisa mengusir tikus tanpa membunuh ekosistemnya.
Ia menanam serai di tepi pematang. Membuat jebakan tikus sederhana dari bambu dan ember. Di tengah sawah, ia dirikan tiang tinggi. Di atasnya, ia bentuk burung elang dari pelepah pisang dan karung goni. Patung itu tidak sempurna, tapi cukup untuk menggetarkan naluri tikus dan menyapa langit yang mulai sepi dari burung.
Hari demi hari, sawahnya mulai pulih. Tikus berkurang, tanah menjadi gembur karena tak terpapar racun. Air mengalir jernih, dan burung-burung kembali. Waktu panen tiba, padi Nang Lecir berdiri gagah, berisi, dan harum.
Tuan Tanah datang, heran melihat hasilnya.
“Lho, Lecir. Kok bisa sawahmu malah paling bagus? Padahal kau tak pakai drone, pupuk cair, atau racun?”
Nang Lecir menatapnya tenang. Ia tahu pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tapi untuk direnungkan.
“Saya bukan menolak teknologi,” ujarnya pelan. “Tapi saya tidak akan membunuh keseimbangan demi hasil cepat. Tanah ini bukan sekadar ladang. Ini warisan. Ini hidup.”
Tuan Tanah terdiam. Di belakangnya, drone masih berdengung, tapi suara itu kini kalah oleh desir angin dan nyanyian burung yang kembali ke langit desa.
Oleh : Ngurah Sigit.
Penulis Adalah : Sosilog. Budayawan dan Pemerhati Media.
What's Your Reaction?